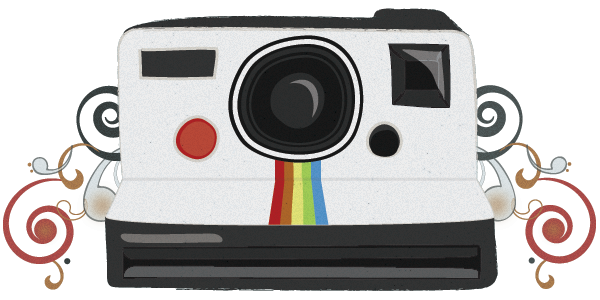Kutemukan satu kisah kesukaanku.. Edgar Allan Poe penulisnya. Karena beliau juga saya tertarik menulis (bakal) novel dengan genre horror klasik seperti ini. Semoga lekas..
Memang benar! Aku gelisah, sangat-sangat gelisah pada waktu itu --
sekarang pun masih. Namun, mengapa kalian menyebutku gila? Rasa sakit
menajamkan inderaku, bukan melemahkannya. Apalagi, membuatnya tumpul.
Dibanding indera lainnya, indera pendengaranku paling tajam. Aku
mendengar semua hal di langit dan di bumi. Aku mendengar suara di
neraka. Bagaimana bisa aku disebut gila? Dengarlah! Kalian akan tahu
betapa warasnya aku. Betapa tenangnya aku. Akan kuceritakan kepada
kalian seluruh detail kejadiannya.
***
Sulit menceritakan bagaimana mula-mula pikiran itu menyusup dalam
benakku. Namun, begitu masuk, pikiran memburuku siang malam. Tak ada
niat dan aku tak ada dendam padanya. Aku mencintai orang tua itu. Ia tak
pernah berbuat salah kepadaku. Juga tak pernah melukai hatiku. Emasnya
pun tak kuinginkan. Kupikir yang menjadi persoalan adalah matanya. Hmm,
ya, matanya! Salah satu bola matanya menyerupai mata burung pemangsa –
mata yang biru dan berselaput. Setiap kali mata itu menatapku, darahku
terasa beku. Dan sedikit demi sedikit -- secara berangsur-angsur -- aku
membulatkan hati untuk membunuhnya. Sehingga, terbebas selamanya dari
sergapan mata burung pemangsa itu.
Di sinilah pangkal soalnya. Kau akan menganggapku gila. Semua orang gila
pasti tidak tahu apa-apa. Namun kau akan melihat bagaimana aku
melakukannya. Kau akan melihat betapa cerdiknya aku menyelesaikan
pekerjaanku -- begitu rapi, terencana. Kemudian, berpura-pura tidak tahu
apa-apa. Aku menjadi lebih manis kepada oang tua itu pada seminggu
terakhir sebelum aku membunuhnya. Setiap malam, menjelang tengah malam,
aku memutar gagang pintu kamarnya dan membukanya -- hmm, begitu
hati-hati. Dan kemudian ketika pintu kamar itu terkuak dan cukup bagiku
untuk memasukkan kepala, kumasukkan lentera berkatup yang kurapatkan
semua lempengan katupnya. Sehingga, tidak ada sinar yang menerobos
keluar dari lentera itu. Lalu, kusorongkan kepalaku ke dalam. Oh, kau
pasti terkejut melihat betapa cerdiknya aku menyusupkan kepala. Semua
kulakukan pelan-pelan, sangat-sangat pelan. Sehingga, tidak mengganggu
tidur orang tua itu. Kuperlukan satu jam untuk menempatkan posisi kepala
sebaik-baiknya di celah pintu. Sehingga, aku bisa leluasa melihat orang
tua itu berbaring di ranjangnya. Nah, bisakah orang gila melakukan
pekerjaan secerdik ini? Dan ketika kepalaku sudah leluasa, aku membuka
katup penutup lentera dengan hati-hati -- begitu hati-hati -- jangan
sampai engsel katupnya berderit. Aku membuka seperlunya saja, cukup agar
seberkas tipis cahaya bisa menerangi mata burung pemangsa itu. Dan
pekerjaan seperti ini kulakukan selama tujuh malam berturut-turut, tiap
datang tengah malam. Namun, selalu kujumpai mata itu tertutup. Dalam
keadaan seperti itu tentu mustahil melanjutkan rencanaku. Karena, bukan
orang tua itu yang membangkitkan marahku. Tapi, mata itu! Pagi harinya,
di saat fajar, sengaja kudatangi kamarnya. Kuajak ia bercakap-cakap,
kusapa namanya penuh semangat. Kutanya pula apa tidurnya nyenyak
semalam. Dengan demikian, kau tahu, diperlukan kecerdasan tertentu pada
si tua itu untuk menduga bahwa setiap malam, tepat pukul dua belas, aku
selalu mengamatinya ketika ia tidur.
Pada malam ke delapan aku membuka pintu lebih hati-hati ketimbang
malam-malam sebelumnya. Jarum menit jam dinding, bahkan lebih cepat
ketimbang gerakan tanganku. Baru pada malam itu aku merasakan begitu
besarnya kekuatanku -- begitu cerdiknya akalku. Hampir aku tidak bisa
menahan luapan perasaan menangku. Membayangkan diriku sendiri sedang
menguakkan pintu, sedikit demi sedikit, dan orang tua itu bahkan tidak
pernah berkhayal tentang apa yang kulakukan dan apa yang kupikirkan. Aku
tergeletak dengan lintasan pikiran ini. Mungkin, ia mendengar suaraku.
Karena, tiba-tiba, ia menggerakkan tubuhnya seperti orang terkejut.
Sekarang kau pasti berpikir bahwa aku akan mundur. Tidak! Kamarnya gelap
pekat, jendelanya tertutup rapat. Karena itu, aku tahu bahwa ia tidak
melihat pintu kamarnya terkuak, dan aku terus saja mendorong daun pintu
itu sedikit demi sedikit.
Aku menyusupkan kepalaku ke celah pintu dan sedang membuka katup
lentera, ketika jempolku tiba-tiba selip dan mengetuk lempengan penutup,
dan si tua itu bangkit dari ranjangnya.
"Siapa itu?" teriaknya.
Aku mematung di tempatku dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam
satu jam aku sama sekali tak bergerak. Selama itu, pula aku tak
mendengar ia merebahkan tubuhnya lagi. Ia tetap duduk di ranjangnya dan
mendengarkan. Seperti aku, malam demi malam. Mendengar detak jam
kematian di dinding.
Tiba-tiba kudengar erangan kecil, dan aku tahu itulah erangan yang
muncul. Karena, teror kematian. Bukan erangan, karena sakit atau
dukacita. Sama sekali bukan. Itu suara lemah orang tercekik. Suara yang
muncul dari dasar jiwa yang diteror kengerian. Aku kenal sekali dengan
suara itu. Beberapa malam, tepat tengah malam, di saat dunia terlelap,
suara itu bangkit dari dadaku, menusuk-nusuk. Gaungnya mengerikan.
Sebuah teror yang menggelisahkan. Kubilang aku kenal betul suara itu.
Aku tahu apa yang dirasakan orang tua itu, dan turut berduka atas
kemalangannya, meskipun dalam hati aku ketawa. Aku tahu bahwa matanya
tak pernah lagi terpejam, sejak ia dikejutkan oleh suara yang
membangunkannya. Rasa takutnya tumbuh semakin besar. Ia coba menenangkan
diri, tapi tidak bisa. Ia yakinkan dirinya sendiri, "Tidak ada apapun,
hanya angin di cerobong asap – hanya tikus yang merayap," atau "hanya
jangkrik yang mengerik." Ya, ia mencoba menenangkan diri dengan
dugaan-dugaan seperti itu, tapi sia-sia. Sia-sia; sebab maut yang
menguntitnya diam-diam kini telah mengepung korbannya dengan
bayang-bayang hitam. Dan efek muram bayang-bayang yang tak tampak itulah
yang menyebabkan ia merasakan -- bukan mendengar atau melihat. Namun
merasakan -- kehadiran kepalaku di kamarnya.
Setelah cukup lama menunggu, dengan sangat sabar, tanpa mendengar ia
membaringkan kembali tubuhnya, maka kubuka sedikit -- sedikit sekali --
katup lentera untuk membuka celah kecil. Kau takkan bisa membayangkan
betapa hati-hatinya aku membuka katup itu. Sehingga, akhirnya seutas
cahaya, setipis sulur benang laba-laba, memancar dari celah lentera dan
jatuh tepat di mata burung pemangsa itu.
Mata itu terbuka, begitu lebar. Amarahku bangkit ketika melihat mata itu
terbuka. Jelas sekali kulihat -- mata biru berkabut, dengan selaput
yang mengerikan, yang menusukkan hawa dingin di sumsum tulangku. Namun,
sama sekali tak kulihat wajah orang tua itu: sebab seolah dibimbing oleh
naluriku, cahaya lentera kuarahkan tepat pada bulatan mata keparat itu.
Jadi, bukanlah yang kau sebut gila itu sesungguhnya adalah inderaku yang
begitu tajam? Sekarang aku mendengar suara lemah, samar-samar, berdetak
dalam tempo cepat seperti detak jam yang terbungkus kain. Aku kenal
betul suara itu. Ialah bunyi detak jantung orang tua itu. Kemarahanku
memuncak, sebagaimana keberanian seorang serdadu naik, karena pukulan
genderang.
Kendati demikian aku masih menahan diri. Kutahan napasku. Kujaga lentera
di tanganku. Kujaga agar sinarnya tetap jatuh ke matanya. Sementara
detak jantung terkutuk itu temponya semakin meningkat. Makin lama makin
cepat, dan makin keras. Ketakutan si tua itu, pastilah luar biasa! Suara
itu makin keras, kubilang, bertambah keras setiap saat. Kau catatkah
omonganku baik-baik? Telah kukatakan kepadamu bahwa aku gelisah:
begitulah yang kurasakan. Dan sekarang pada jam kematian malam itu, di
tengah kebisuan yang mencekam di rumah tua itu, dentam aneh itu
menyiksaku layaknya sebuah teror yang tak tertanggungkan. Aku masih
menahan diri beberapa menit dan tetap tak beraksi. Namun, dentam itu
makin memekakkan. Kupikir jantungnya pasti segera meledak. Dan sekarang
aku merasakan kecemasan baru -- para tetangga pasti akan mendengar bunyi
itu! Tiba sudah waktu bagi si tua! Dengan teriakan keras, aku membuka
semua katup lentera dan merangsek masuk ke dalam kamar. Sekali ia
memekik, hanya sekali. Dalam sekejap aku menyeretnya ke lantai dan
membekapnya dengan kasur tebalnya. Setelah itu, senyumku mengembang,
semua pekerjaan beres. Bermenit-menit jantung itu masih berdetak
samar-samar. Namun, tak lagi membuatku jengkel. Suaranya takkan mampu
menembus dinding. Akhirnya bunyi itu berhenti. Si tua mati. Aku
mengangkat kasur dan memeriksa mayatnya. Ya, ia sudah mati. Matanya
takkan menyusahkan aku lagi.
Kalau masih kau anggap gila aku, anggapan itu tak akan berlaku lagi bila
kulukiskan apa yang kulakukan untuk menyembunyikan mayatnya. Malam
melarut, dan aku mengebut pekerjaanku, tanpa suara. Pertama-tama
kumutilasi mayat itu. Kupenggal kepalanya, kedua lengannya, dan kedua
kakinya.
Kemudian, kubongkar tiga bilah papan lantai kamar itu dan kumasukkan
potongan-potongan tubuhnya ke dalam rongga di bawah lantai kamar.
Setelah itu kukembalikan lagi papan lantai seperti semula, begitu
sepele, begitu rapi. Sehingga, tak satupun mata -- termasuk mata si tua
itu -- yang menemukan adanya kejanggalan. Tak ada yang perlu dicuci.
Karena, tak ada ceceran noda apa pun. Tak ada bercak darah sekecil apa
pun. Aku sangat waspada terhadap semua itu. Bak mandi sudah menampung
semuanya. Ha! Ha!
Jam empat pagi semua pekerjaanku selesai sudah. Hari masih gelap seperti
tengah malam. Bersamaan dengan dentang lonceng jam, terdengar ketukan
di pintu depan. Aku turun dengan perasaan ringan. Apalagi, yang perlu
ditakutkan kini? Kubuka pintu, tiga orang lelaki masuk. Mereka
memperkenalkan diri dengan sangat sopan sebagai petugas-petugas
kepolisian. Seorang tetangga mendengar pekik si tua itu semalam. Menduga
ada tindak kejahatan, ia melapor kantor polisi. Dan mereka (para polisi
itu) ditugasi untuk melakukan penyidikan atas kecurigaan si tetangga.
Aku tersenyum. Apalagi, yang perlu ditakutkan? Dengan ramah kupersilakan
mereka masuk. Pekik itu, kataku, keluar dari mulutku di saat mimpi.
Kujelaskan kepada mereka bahwa si orang tua sedang tidak di rumah. Lalu,
kubawa mereka melihat-lihat seisi rumah. Kupersilakan mereka memeriksa
-- memeriksa dengan teliti. Akhirnya, kubawa ketiga orang itu ke kamar
si tua. Kuperlihatkan kepada mereka barang-barang berharga miliknya.
Semua aman, tak tercolek. Dengan kepercayaan diri yang melambung, aku
mengusung kursi-kursi ke dalam kamar itu. Dan meminta mereka untuk
melepas lelah di tempat itu. Sementara aku sendiri, dalam gelegak
keberanian, karena kemenangan yang sempurna, meletakkan kursiku tepat di
atas tempat aku menyimpan mayat si tua.
Para petugas merasa puas. Perlakuanku meyakinkan mereka. Aku sendiri
merasa tenang. Mereka duduk. Sementara aku menjawab
pertanyaan-pertanyaan dengan keseharian yang normal. Tapi, sebentar
kemudian aku merasa parasku memucat dan berharap agar mereka segera
pergi. Kepalaku pening, dan aku merasakan penging di telingaku. Namun,
mereka tetap duduk dan bercakap-cakap. Suara penging itu makin jelas:
terus-menerus dan makin jelas. Aku bicara lebih keras untuk mengusir
perasaan itu. Namun, suara penging itu terus saja dan makin pasti.
Sampai akhirnya aku sadar bahwa suara penging itu bukan di dalam
telingaku.
Parasku, aku yakin makin memucat. Namun, bicaraku lebih fasih dan lebih
lantang. Suara penging itu "bangkit". Aduh, apa yang bisa kulakukan?
Kudengar suara lemah, samar-samar, yang berdetak dalam tempo cepat.
Seperti, detak jam yang terbungkus kain. Napasku tersengal. Namun, para
petugas itu tidak mendengarnya. Bicaraku lebih cepat, lebih meyakinkan.
"Bebunyian" keparat itu makin kuat. Aku bangkit dan mendebat segala
topik pembicaraan yang sepele, dalam nada tinggi dan gerak tubuh yang
kasar. Dan bunyi itu terus menguat.
Mengapa mereka tidak mau pergi? Aku mondar-mandir dengan langkah panjang
dan menghentak. Seolah-olah merasa terganggu oleh pemeriksaan yang
mereka lakukan. Tapi, bunyi keparat itu terus menguat. Ya, Tuhan! Apa
yang bisa kulakukan? Aku meradang. Aku meracau. Aku mengutuk! Kuangkat
kursi yang kududuki dan kuhempaskan benda itu ke lantai papan. Namun,
kegaduhan yang ditimbulkanya tertelan oleh bunyi detak keparat yang
terus menguat itu. Suara itu makin kencang, makin kencang, makin
kencang! Para petugas, tetap melanjutkan percakapan seperti tak terjadi
apa-apa. Mereka cuma tersenyum. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar
suara itu? Demi Tuhan! Tidak! Tidak! Mereka juga mendengar. Mereka
curiga. Mereka tahu! Mereka pasti sedang menemoohkan ketakutanku.
Kupikir begitu. Cara lain kurasa jauh lebih baik dari siksaan seperti
ini! Cara lain apa pun lebih bisa ditanggungkan daripada pelecehan ini!
Aku tidak kuat lagi melihat senyum pura-pura mereka. Aku merasa bahwa
aku harus berteriak. Atau aku mampus! Dan sekarang, bunyi itu lagi.
Dengar! Makin kencang. Makin kencang. Makin kencang!
"Jahanam!" aku memekik, "tak usah berpura-pura lagi! Aku yang melakukan
semuanya! Bongkar saja papan ini di sini, di sini! Di sinilah dentam
jantung keparat itu!"