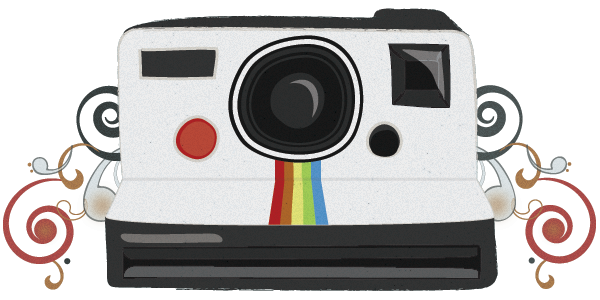Malam bertambah malam. Pagi terlalu pagi.
Karena sejatinya pikiran kita kala dini hari adalah pikiran yang tak terhentikan. Liar, brutal, beringas. Torehkan apa yang ingin dikeluarkan oleh kalian. Lawan semua rasa ngantuk. Berbahagialah dalam ketersiksaan. Kamu tidak bermimpi, kamu ingin menuliskan mimpimu.
Cintailah dini hari!
Archive for Januari 2014
Orang kecil berbahagialah dalam ketiadaan.
Ketertarikanku akhir-akhir pada bio twitter yang ku tulis. Aku menyukai kata-kata itu. "Orang kecil kembalilah dalam ketiadaan." Kata-kata Soe dalam menit-menit terakhir menuju kredit di film GIE. Soe Hok Gie, pemikirannya beringas di awal, benar di perjalanan, miris di akhir. Itu yang kurasakan dalam perjalanan film itu.
Posisi yang tepat di mata khalayak umum adalah puncak apalagi sentral. Berbeda dengan pandangan orang umum. Posisi paling cocok untukku adalah bawah ataupun tepi. Di sana kutemukan bahwa sejatinya aku tercipta (entah) untuk posisi itu atau di posisi tersebut.
Beberapa orang tidak bisa memimpin, tapi beberapa orang lebih bisa mempengaruhi. Suatu kebetulan apabila aku tidak pernah menjadi posisi sentral. Kala itu aku bisa saja menjadi anggota OSIS, wali kelas tidak merekomendasi. Lain waktu aku bisa saja menjadi ketua kelas, kebetulan wali kelas lebih memilih menjadi sie kebersihan. Beberapa saat mereka mendukungku dalam suatu pekerjaan. Ya aku sanggupi tapi tidak maksimal, karena saat itu pula aku mulai menyukai individualis dalam pekerjaan (yang aku bisa). Tidak semua kuiyakan. Lalu beberapa kesempatan aku menepi. Kebetulan juga aku bisa menjadi seorang pemimpin dalam suatu kelompok, dan kala itu aku belum menyadari posisi favoritku: tepi.
Tapi kalau kebetulan itu terlalu banyak dan kebetulan-kebetulan itu saling berkaitan, apakah kebetulan itu kebetulan? Atau lebih ke suatu yang sudah ditorehkan oleh Hyang Suci?
Sifat dasar manusia generasi ini adalah cari nyaman. Begitu pula denganku. Tapi beberapa orang pula cari enak. Enak, berbeda dengan nyaman. Enak, ketika kau mendapat posisi yang memberimu sentral dalam segala hal, tapi terancam dalam memutuskan. Nyaman, apabila kau memiliki posisi yang membuatmu leluasa dalam segala hal, tapi selalu menerima resiko di atas.
Enak itu orang-orang atas.
Nyaman itu orang-orang bawah.
Enak itu Goliath.
Nyaman itu Daud.
Mereka--kami. Aku senang apabila pikiran-pikiranku ini bisa menghibur mereka yang di atas, apalagi bisa mempengaruhi keputusan di atas. Pernah ku berbicara saat pelatihan Pasus (Pasukan Khusus) kala itu aku ditanyai akan jadi apa dalam sebuah organisasi. Wakil ketua, jawabku. Dan aku baru menyadari arti itu.
How does it feel
with no direction home
like a complete unknown,
like a rolling stone?
Lirik dari Bob Dylan pun juga menyentil telingaku. Seperti anon yang komplit. Seperti batu yang berguling. Ya kan? Yang kusukai dari anon adalah peka, di satu sisi orang yang tidak peka tak akan tahu jika kalimat yang dilontarkan untuknya adalah nyinyir atau tidak.
Ret-Ret
Mencari kesejatian diri. Itulah yang mereka cari. Mulai dari orang-orang beragama, orang-orang bertuhan, bahkan sampai orang kafir pun sebenarnya mencari kesejatian diri. Budha, Muslim, Katolik pun mencari! Masalahnya, apa benar kita dapat menerima dengan lapang dada ketika sudah mengetahui diri kita yang sejati? Meditasi, kontemplasi, ketahui lalu syukuri. Setidaknya itu tahap-tahap untuk mengenal, karena diri kita yang bertopeng ini terkadang tidak suka dengan diri kita yang utuh.
Lalu?
Nek motormu
regane sak mobil,
njuk?
Nek hapemu
merek buah,
njuk?
Nek celanamu pensil,
njuk?
Kere? Yo ben!
Uripmu sekedar gengsi.
Njijiki!