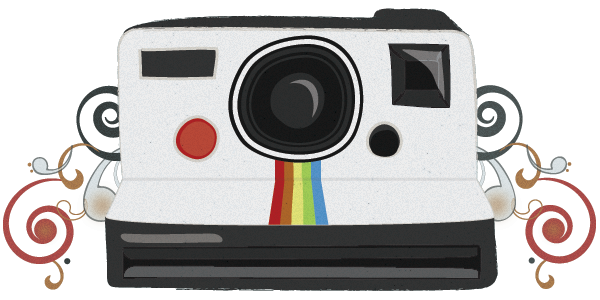Banyak hal yang semua orang targetkan. Mulai dari jodoh, hasil yang memuaskan, sampai pada kemenangan akan jabatan yang masing-masing harapkan. Semua pada kepuasan tersendiri tentunya, dan jarang ada orang yang menargetkan tentang kenegatifan, kecuali manusia-manusia jihad, Taliban dan sebagainya.
Yang kumaksud disini dengan target bunuh diriku, bukan berarti aku menginginkan kematian lebih cepat dari waktunya, semuanya sudah ditetapkan Maha Oke dan biarlah Beliau yang mengurus itu. Kegiatan teater yang akhir-akhir ini semakin ketat, dan lama-kelamaan aku mencintai sesuatu hal bernama Waktu, aku memprioritaskannya akhir-akhir ini..
Ya, saya cinta teater, bisa dibilang begitu. Karena saya sangat-sangat jenuh dengan semua kebohongan dan kehidupan penuh dosa, apalagi kehidupan sekolah yang lama-lama tidak logis untuk dijalani. Bayangkan satu minggu, kita diberi tugas, praktikum, presentasi, ulangan, dan segala macam kuis dalam satu minggu. Buat apa kita dituntut belajar semua mata pelajaran, kalau sebenarnya pengampu tidak paham semua pelajaran yang murid terima? Mungkin profesi guru merupakan ajang balas dendam para mantan murid, mungkin ya? Saya lebih terima nantinya saya di api pencucian (kalau misalkan itu ada) daripada berkhayal langsung masuk surga dengan adem ayem. Munafik sekali ya orang-orang macam itu?
Untuk cinta pada teater dan korelasi tentang target bunuh diriku, intinya aku akan melancarkan semua dialog sarkasme untuk para pejabat-pejabat biadab. Kegiatan penyadaran, istilahnya.. Tapi apabila pejabat yang berotak udang itu malah tersindir, ini yang kuharapkan. Reaksi pejabat itu yang kuharapkan, memerintah bodyguard/polisi dan segala macam profesi dengan kedok penegak keadilan lainnya, untuk menangkapku, menuntutku, dan memenjarakanku, harapannya..
Ya namanya harapan juga masih semacam Visi kan yak? Analoginya kita mendapat juara harapan satu, ya artinya kita sebenarnya bisa juara satu. Salahnya, di Indonesia (di dunia mungkin juga ya?), juara harapan satu malah sebagai juara empat. Tolol kan?
Ya, jadi aku hanya ingin bercerita bahwa aku sudah menargetkan diriku, seusai pentas teater November 2013 ini, aku bisa dituntut oleh pejabat, dipenjarakan kalau perlu.
Wasalam!
Archive for Oktober 2013
Detak Jantung dan Hati yang Meracau
Kutemukan satu kisah kesukaanku.. Edgar Allan Poe penulisnya. Karena beliau juga saya tertarik menulis (bakal) novel dengan genre horror klasik seperti ini. Semoga lekas..
***
Sulit menceritakan bagaimana mula-mula pikiran itu menyusup dalam benakku. Namun, begitu masuk, pikiran memburuku siang malam. Tak ada niat dan aku tak ada dendam padanya. Aku mencintai orang tua itu. Ia tak pernah berbuat salah kepadaku. Juga tak pernah melukai hatiku. Emasnya pun tak kuinginkan. Kupikir yang menjadi persoalan adalah matanya. Hmm, ya, matanya! Salah satu bola matanya menyerupai mata burung pemangsa – mata yang biru dan berselaput. Setiap kali mata itu menatapku, darahku terasa beku. Dan sedikit demi sedikit -- secara berangsur-angsur -- aku membulatkan hati untuk membunuhnya. Sehingga, terbebas selamanya dari sergapan mata burung pemangsa itu.
Di sinilah pangkal soalnya. Kau akan menganggapku gila. Semua orang gila pasti tidak tahu apa-apa. Namun kau akan melihat bagaimana aku melakukannya. Kau akan melihat betapa cerdiknya aku menyelesaikan pekerjaanku -- begitu rapi, terencana. Kemudian, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku menjadi lebih manis kepada oang tua itu pada seminggu terakhir sebelum aku membunuhnya. Setiap malam, menjelang tengah malam, aku memutar gagang pintu kamarnya dan membukanya -- hmm, begitu hati-hati. Dan kemudian ketika pintu kamar itu terkuak dan cukup bagiku untuk memasukkan kepala, kumasukkan lentera berkatup yang kurapatkan semua lempengan katupnya. Sehingga, tidak ada sinar yang menerobos keluar dari lentera itu. Lalu, kusorongkan kepalaku ke dalam. Oh, kau pasti terkejut melihat betapa cerdiknya aku menyusupkan kepala. Semua kulakukan pelan-pelan, sangat-sangat pelan. Sehingga, tidak mengganggu tidur orang tua itu. Kuperlukan satu jam untuk menempatkan posisi kepala sebaik-baiknya di celah pintu. Sehingga, aku bisa leluasa melihat orang tua itu berbaring di ranjangnya. Nah, bisakah orang gila melakukan pekerjaan secerdik ini? Dan ketika kepalaku sudah leluasa, aku membuka katup penutup lentera dengan hati-hati -- begitu hati-hati -- jangan sampai engsel katupnya berderit. Aku membuka seperlunya saja, cukup agar seberkas tipis cahaya bisa menerangi mata burung pemangsa itu. Dan pekerjaan seperti ini kulakukan selama tujuh malam berturut-turut, tiap datang tengah malam. Namun, selalu kujumpai mata itu tertutup. Dalam keadaan seperti itu tentu mustahil melanjutkan rencanaku. Karena, bukan orang tua itu yang membangkitkan marahku. Tapi, mata itu! Pagi harinya, di saat fajar, sengaja kudatangi kamarnya. Kuajak ia bercakap-cakap, kusapa namanya penuh semangat. Kutanya pula apa tidurnya nyenyak semalam. Dengan demikian, kau tahu, diperlukan kecerdasan tertentu pada si tua itu untuk menduga bahwa setiap malam, tepat pukul dua belas, aku selalu mengamatinya ketika ia tidur.
Pada malam ke delapan aku membuka pintu lebih hati-hati ketimbang malam-malam sebelumnya. Jarum menit jam dinding, bahkan lebih cepat ketimbang gerakan tanganku. Baru pada malam itu aku merasakan begitu besarnya kekuatanku -- begitu cerdiknya akalku. Hampir aku tidak bisa menahan luapan perasaan menangku. Membayangkan diriku sendiri sedang menguakkan pintu, sedikit demi sedikit, dan orang tua itu bahkan tidak pernah berkhayal tentang apa yang kulakukan dan apa yang kupikirkan. Aku tergeletak dengan lintasan pikiran ini. Mungkin, ia mendengar suaraku. Karena, tiba-tiba, ia menggerakkan tubuhnya seperti orang terkejut. Sekarang kau pasti berpikir bahwa aku akan mundur. Tidak! Kamarnya gelap pekat, jendelanya tertutup rapat. Karena itu, aku tahu bahwa ia tidak melihat pintu kamarnya terkuak, dan aku terus saja mendorong daun pintu itu sedikit demi sedikit.
Aku menyusupkan kepalaku ke celah pintu dan sedang membuka katup lentera, ketika jempolku tiba-tiba selip dan mengetuk lempengan penutup, dan si tua itu bangkit dari ranjangnya.
"Siapa itu?" teriaknya.
Aku mematung di tempatku dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam satu jam aku sama sekali tak bergerak. Selama itu, pula aku tak mendengar ia merebahkan tubuhnya lagi. Ia tetap duduk di ranjangnya dan mendengarkan. Seperti aku, malam demi malam. Mendengar detak jam kematian di dinding.
Tiba-tiba kudengar erangan kecil, dan aku tahu itulah erangan yang muncul. Karena, teror kematian. Bukan erangan, karena sakit atau dukacita. Sama sekali bukan. Itu suara lemah orang tercekik. Suara yang muncul dari dasar jiwa yang diteror kengerian. Aku kenal sekali dengan suara itu. Beberapa malam, tepat tengah malam, di saat dunia terlelap, suara itu bangkit dari dadaku, menusuk-nusuk. Gaungnya mengerikan. Sebuah teror yang menggelisahkan. Kubilang aku kenal betul suara itu. Aku tahu apa yang dirasakan orang tua itu, dan turut berduka atas kemalangannya, meskipun dalam hati aku ketawa. Aku tahu bahwa matanya tak pernah lagi terpejam, sejak ia dikejutkan oleh suara yang membangunkannya. Rasa takutnya tumbuh semakin besar. Ia coba menenangkan diri, tapi tidak bisa. Ia yakinkan dirinya sendiri, "Tidak ada apapun, hanya angin di cerobong asap – hanya tikus yang merayap," atau "hanya jangkrik yang mengerik." Ya, ia mencoba menenangkan diri dengan dugaan-dugaan seperti itu, tapi sia-sia. Sia-sia; sebab maut yang menguntitnya diam-diam kini telah mengepung korbannya dengan bayang-bayang hitam. Dan efek muram bayang-bayang yang tak tampak itulah yang menyebabkan ia merasakan -- bukan mendengar atau melihat. Namun merasakan -- kehadiran kepalaku di kamarnya.
Setelah cukup lama menunggu, dengan sangat sabar, tanpa mendengar ia membaringkan kembali tubuhnya, maka kubuka sedikit -- sedikit sekali -- katup lentera untuk membuka celah kecil. Kau takkan bisa membayangkan betapa hati-hatinya aku membuka katup itu. Sehingga, akhirnya seutas cahaya, setipis sulur benang laba-laba, memancar dari celah lentera dan jatuh tepat di mata burung pemangsa itu.
Mata itu terbuka, begitu lebar. Amarahku bangkit ketika melihat mata itu terbuka. Jelas sekali kulihat -- mata biru berkabut, dengan selaput yang mengerikan, yang menusukkan hawa dingin di sumsum tulangku. Namun, sama sekali tak kulihat wajah orang tua itu: sebab seolah dibimbing oleh naluriku, cahaya lentera kuarahkan tepat pada bulatan mata keparat itu.
Jadi, bukanlah yang kau sebut gila itu sesungguhnya adalah inderaku yang begitu tajam? Sekarang aku mendengar suara lemah, samar-samar, berdetak dalam tempo cepat seperti detak jam yang terbungkus kain. Aku kenal betul suara itu. Ialah bunyi detak jantung orang tua itu. Kemarahanku memuncak, sebagaimana keberanian seorang serdadu naik, karena pukulan genderang.
Kendati demikian aku masih menahan diri. Kutahan napasku. Kujaga lentera di tanganku. Kujaga agar sinarnya tetap jatuh ke matanya. Sementara detak jantung terkutuk itu temponya semakin meningkat. Makin lama makin cepat, dan makin keras. Ketakutan si tua itu, pastilah luar biasa! Suara itu makin keras, kubilang, bertambah keras setiap saat. Kau catatkah omonganku baik-baik? Telah kukatakan kepadamu bahwa aku gelisah: begitulah yang kurasakan. Dan sekarang pada jam kematian malam itu, di tengah kebisuan yang mencekam di rumah tua itu, dentam aneh itu menyiksaku layaknya sebuah teror yang tak tertanggungkan. Aku masih menahan diri beberapa menit dan tetap tak beraksi. Namun, dentam itu makin memekakkan. Kupikir jantungnya pasti segera meledak. Dan sekarang aku merasakan kecemasan baru -- para tetangga pasti akan mendengar bunyi itu! Tiba sudah waktu bagi si tua! Dengan teriakan keras, aku membuka semua katup lentera dan merangsek masuk ke dalam kamar. Sekali ia memekik, hanya sekali. Dalam sekejap aku menyeretnya ke lantai dan membekapnya dengan kasur tebalnya. Setelah itu, senyumku mengembang, semua pekerjaan beres. Bermenit-menit jantung itu masih berdetak samar-samar. Namun, tak lagi membuatku jengkel. Suaranya takkan mampu menembus dinding. Akhirnya bunyi itu berhenti. Si tua mati. Aku mengangkat kasur dan memeriksa mayatnya. Ya, ia sudah mati. Matanya takkan menyusahkan aku lagi.
Kalau masih kau anggap gila aku, anggapan itu tak akan berlaku lagi bila kulukiskan apa yang kulakukan untuk menyembunyikan mayatnya. Malam melarut, dan aku mengebut pekerjaanku, tanpa suara. Pertama-tama kumutilasi mayat itu. Kupenggal kepalanya, kedua lengannya, dan kedua kakinya.
Kemudian, kubongkar tiga bilah papan lantai kamar itu dan kumasukkan potongan-potongan tubuhnya ke dalam rongga di bawah lantai kamar. Setelah itu kukembalikan lagi papan lantai seperti semula, begitu sepele, begitu rapi. Sehingga, tak satupun mata -- termasuk mata si tua itu -- yang menemukan adanya kejanggalan. Tak ada yang perlu dicuci. Karena, tak ada ceceran noda apa pun. Tak ada bercak darah sekecil apa pun. Aku sangat waspada terhadap semua itu. Bak mandi sudah menampung semuanya. Ha! Ha!
Jam empat pagi semua pekerjaanku selesai sudah. Hari masih gelap seperti tengah malam. Bersamaan dengan dentang lonceng jam, terdengar ketukan di pintu depan. Aku turun dengan perasaan ringan. Apalagi, yang perlu ditakutkan kini? Kubuka pintu, tiga orang lelaki masuk. Mereka memperkenalkan diri dengan sangat sopan sebagai petugas-petugas kepolisian. Seorang tetangga mendengar pekik si tua itu semalam. Menduga ada tindak kejahatan, ia melapor kantor polisi. Dan mereka (para polisi itu) ditugasi untuk melakukan penyidikan atas kecurigaan si tetangga.
Aku tersenyum. Apalagi, yang perlu ditakutkan? Dengan ramah kupersilakan mereka masuk. Pekik itu, kataku, keluar dari mulutku di saat mimpi. Kujelaskan kepada mereka bahwa si orang tua sedang tidak di rumah. Lalu, kubawa mereka melihat-lihat seisi rumah. Kupersilakan mereka memeriksa -- memeriksa dengan teliti. Akhirnya, kubawa ketiga orang itu ke kamar si tua. Kuperlihatkan kepada mereka barang-barang berharga miliknya. Semua aman, tak tercolek. Dengan kepercayaan diri yang melambung, aku mengusung kursi-kursi ke dalam kamar itu. Dan meminta mereka untuk melepas lelah di tempat itu. Sementara aku sendiri, dalam gelegak keberanian, karena kemenangan yang sempurna, meletakkan kursiku tepat di atas tempat aku menyimpan mayat si tua.
Para petugas merasa puas. Perlakuanku meyakinkan mereka. Aku sendiri merasa tenang. Mereka duduk. Sementara aku menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan keseharian yang normal. Tapi, sebentar kemudian aku merasa parasku memucat dan berharap agar mereka segera pergi. Kepalaku pening, dan aku merasakan penging di telingaku. Namun, mereka tetap duduk dan bercakap-cakap. Suara penging itu makin jelas: terus-menerus dan makin jelas. Aku bicara lebih keras untuk mengusir perasaan itu. Namun, suara penging itu terus saja dan makin pasti. Sampai akhirnya aku sadar bahwa suara penging itu bukan di dalam telingaku.
Parasku, aku yakin makin memucat. Namun, bicaraku lebih fasih dan lebih lantang. Suara penging itu "bangkit". Aduh, apa yang bisa kulakukan? Kudengar suara lemah, samar-samar, yang berdetak dalam tempo cepat. Seperti, detak jam yang terbungkus kain. Napasku tersengal. Namun, para petugas itu tidak mendengarnya. Bicaraku lebih cepat, lebih meyakinkan. "Bebunyian" keparat itu makin kuat. Aku bangkit dan mendebat segala topik pembicaraan yang sepele, dalam nada tinggi dan gerak tubuh yang kasar. Dan bunyi itu terus menguat.
Mengapa mereka tidak mau pergi? Aku mondar-mandir dengan langkah panjang dan menghentak. Seolah-olah merasa terganggu oleh pemeriksaan yang mereka lakukan. Tapi, bunyi keparat itu terus menguat. Ya, Tuhan! Apa yang bisa kulakukan? Aku meradang. Aku meracau. Aku mengutuk! Kuangkat kursi yang kududuki dan kuhempaskan benda itu ke lantai papan. Namun, kegaduhan yang ditimbulkanya tertelan oleh bunyi detak keparat yang terus menguat itu. Suara itu makin kencang, makin kencang, makin kencang! Para petugas, tetap melanjutkan percakapan seperti tak terjadi apa-apa. Mereka cuma tersenyum. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar suara itu? Demi Tuhan! Tidak! Tidak! Mereka juga mendengar. Mereka curiga. Mereka tahu! Mereka pasti sedang menemoohkan ketakutanku. Kupikir begitu. Cara lain kurasa jauh lebih baik dari siksaan seperti ini! Cara lain apa pun lebih bisa ditanggungkan daripada pelecehan ini! Aku tidak kuat lagi melihat senyum pura-pura mereka. Aku merasa bahwa aku harus berteriak. Atau aku mampus! Dan sekarang, bunyi itu lagi. Dengar! Makin kencang. Makin kencang. Makin kencang!
"Jahanam!" aku memekik, "tak usah berpura-pura lagi! Aku yang melakukan semuanya! Bongkar saja papan ini di sini, di sini! Di sinilah dentam jantung keparat itu!"
Poe
Aku ingin menulis sebuah novel yang berbeda dengan novel-novel Indonesia biasanya. Aku sudah memiliki pikiran ini sejak umurku masih--kira-kira 13 tahun--belum layak berpikiran seperti ini dan aku sudah mempunyai satu folder khusus untuk penulisan novel ini. Belum kupastikan apa judulnya, tapi kemungkinan nama Caesar, Caesarion maupun Ptolemy akan masuk di cerita-cerita dalam novel ini.
The Emptiness. Album dari Alesana yang membuatku tertarik menulis novel. Dari sekedar mendengar lagu-lagu tersebut, sampai aku menemukan sebuah kebenaran dimana 12 lagu-lagu tersebut saling berkaitan dan membentuk sebuah cerita yang satu. Dennis Lee, growl vocalist, yang menulis cerpen itu sebelum mereka membuat album tersebut.
Dari cerpen yang ditulis Dennis Lee itu pula, aku mencari-cari bahwa ada faktor P, mengapa Dennis Lee menulis cerpen itu.. Dikatakan bahwa Dennis Lee juga tertarik oleh cerpen Edgar Allan Poe. Faktor P, ya faktor Poe. Nah, dari situ aku memulai pencarian cerpen-cerpen milik Poe sebagai referensi, yang nantinya menuntunku dalam penulisan novel ini.
Ayah membantai keluarganya sendiri macam kepala suku yang membantai klan yang diciptakannya sendiri. Dia membunuh semua yang dia lihat. Mulai dari perempuan yang dia lihat pertama kali saat ...
Hari itu aku juga belajar bentuk tubuh manusia. Luar dalam. Karena saat itu juga aku baru melihat secara nyata apa itu kolon, apa itu usus halus. Kolon, itu dipakai untuk membunuh semua saudariku. Menggantung mereka semua hingga kehabisan nafas. Tercekik oleh jonjot-jonjot penyerapan pencernaan itu....
Itu dua potong cerita dalam novel yang kelak akan di-publish dan membuat perbedaan sastra di negara ini. Selain itu, aku membuat label Poe untuk nantinya sebagai latihan menulis cerita Horror Gothic yang menyinggung tentang kerusakan psikologi orang..
Kerugian Murah.
Hampir sebulan lalu, kami baru saja berganti pacar, ketika sebenarnya kami tidak ingin berpisah dengan mantan kami. Tetapi semacam Ibu-tak-pernah-hamil mantan kami mencari masalah, lalu kita memutuskan mencari yang namanya hampir sama, bedanya cuma ada digit di belakangnya.
Harapan yang sangat tinggi sudah kami gantungkan untuk mereka yang mendapat kesempatan bersama kami. Kami saling mengincar dan sharing mana saja yang akan di-eksekusi, maksudnya agar tidak ada crash satu sama lain. Dan beberapa pacar kami mundur dengan alasan-alasan yang wagu dan asu.
Permainan yang kami mainkan bersama sudah cocok. Lalu lambat laun sifatnya keluar yang asli. Murah. Kami yang terbiasa mengusahakan, mengejar, eh malah kita yang dikejar, diusahakan. Nahlo?
Murah yang biasanya di-stereotype-kan dengan keuntungan, tapi malah berkebalikan. Ya, kami mengalami kerugian. Belum jelas? Pikirlah lagi. Kami juga berharap tak ada yang merasa tersindir, toh intinya kami tak pernah menyebut nama. Karena sejatinya Kecut itu kata dasar dari Pengecut.
Sekian. Saya tidak ingin share semuanya, toh kami sebagai kelompok senior sudah membicarakan hal ini. Dan. Kami. Jijik. Jadi intinya kerugian murah itu .. jijik.
Wassalam!
Untuk Seseorang..
Untuk seseorang yang terpaksa kita harus putus hubungan ketika aku berpindah kota. Sudah tiga tahun dan aku masih saja ingin mengambil pecahan hati yang masih terbawa.
Sedikit cerita bahwa aku masih ingin. Tapi semesta belum berkenan.
Mungkin kelak, ya?
I never see again pretty eyes, since the last time I saw your eyes. I never kissed again sweet lips, Since the last time I kissed your lips. Go go go go go go, things so fine before yo go. No no no no no no, well did I want it that way, the answer is no. The good old days has ended someway, it's not easy but this the only way. I never knew I’m so lucky to have you, until the day I’ve lost you, parallel life I’ll see you soon...